Oleh : Damasus
Pitriarka Karuniawan Turut
(Guru SD Katolik
Coal)
CAKRAWALANTT.COM - Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 telah mengantar sekolah
memasuki konteks pendidikan abad 21 dengan tiga fokus kecakapan, yakni literasi,
kompetensi dan karakter. Paradigma pendidikan Indonesia menjadi lebih terbuka
terhadap dinamika perubahan. Dalam implementasinya, ada gerakan literasi yang
sudah berjalan lebih dari lima tahun dengan giat aktivitas 6 komponen literasi
dasar, yakni kemampuan baca-tulis, berhitung, sains, teknologi informasi dan
komunikasi, keuangan, budaya dan kewarganegaraan. Ekspetasi dari gerakan tersebut tentunya bertujuan untuk
membentuk individu berkualitas dalam berbagai dimensi kehidupan secara
komprehensif.
Tidak dapat dipungkiri, peserta didik sekarang
menjadi bagian dari generasi digital
native karena telah mengenal fitur digital sejak dini (Kemendikbud,
2016:9). Di sisi lain, akses pemahaman terhadap konsep literasi tetap perlu
dikontrol. Di tengah upaya membangun keutuhan paradigma literasi, berbagai
fenomena tampak mengkhawatirkan dan membuat resah ekosistem sekolah. Penulis
melihat potret faktual bagaimana peserta didik terjebak dalam satu konsep semu
literasi. Pengaruh “medan magnet digital”
telah menarik peserta didik ke pengalaman yang sangat luas, bahkan di luar
konteks pembelajaran.
Fenomena ini dapat saja dimaknai sebagai sebuah
upaya adaptasi terhadap perubahan zaman. Namun, bagaimana melihat aktualisasi
literasi yang seimbang di antara keenam komponen yang ada? Apakah literasi
budaya juga digiatkan selain teknologi dan informasi? Menyebut contoh, apakah peserta didik
memiliki pengetahuan tentang tombo turuk/
nunduk (dongeng) Manggarai?
Peserta didik memiliki kecenderungan mengabaikan kekayaan
budaya lokal dan asyik menyelam dalam dunia teknologi digital. Dengan kata
lain, tidak mengherankan bila topik tentang free
fire, menjadi wujud ‘dongeng milenial’ yang banyak dibicarakan. Jika
kembali bercermin pada ketiga fokus kecakapan di atas, maka sangatlah urgen
untuk menyeimbangkan implementasi semua komponen literasi.
Masalah ini juga penulis temukan di kelas V SD
Katolik Coal melalui observasi terbuka, dimana peserta didik lebih cenderung
menceritakan pengalaman maya. Misalnya, peserta didik laki-laki asyik bercerita
tentang konten game dan peserta didik
wanita bercerita tentang isi sinema elektronik. Fakta ini hampir terjadi setiap
hari di saat jeda pembelajaran.
Jerome Bruner menekankan adanya pengaruh kebudayaan
terhadap tingkah laku seseorang. Proses belajar akan berjalan dengan baik dan
kreatif bila guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan
suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai
dalam kehidupannya melalui contoh-contoh konkret yang menggambarkan aturan sebagai
sumbernya (Dirman & Juarsih, 2014: 23).
Memahami budaya menjadi bagian dari desain
pembelajaran wajib bagi peserta didik di era globalisasi sekarang ini. Literasi
budaya adalah kemampuan untuk mengetahui budaya yang dimiliki bangsa baik
kearifan lokal maupun nasional serta kemampuan dan keinginan untuk melestarikan
serta mengembangkan kebudayaan tersebut (Jendela Pendidikan dan Kebudayaan,
2016:7).
Melihat Indonesia yang strategis karena memiliki kekayaan
budaya berupa ragam suku, adat istiadat, bahasa, kebiasaan, dan komunitas
sosial, maka dengan berliterasi budaya peserta didik dapat mengambil bagian
mencegah lunturnya budaya nasional dari ekspansi budaya global yang kuat.
Dalam aktivitas pembelajaran, penulis bersama peserta
didik mencoba menggali kembali satu unsur kearifan lokal dalam konteks budaya
Manggarai. Unsur kearifan lokal yang
dimaksud adalah dongeng (tombo
turuk/nunduk) atau cerita-cerita rakyat. Cerita yang biasa dilisankan
tersebut secara operasional dihidupkan dalam nuansa pembelajaran di sekolah.
Dongeng memiliki kekuatan membelajarkan peserta didik tentang makna, nilai,
perilaku, karakter, serta fenomena sosial yang bercermin pada kisah dan tokoh.
Menginternalisasi makna-makna tersebut membantu
peserta didik sukses dalam hidup dan menghindarkan mereka dari perilaku
menyimpang seperti licik, pengecut, menipu, dan sebagainya (Terrell A. Young,
dkk., 2010:15). Dongeng-dongeng Manggarai pun demikian, kaya makna budaya dan
mudah dipahami nilainya.
Langkah awal yang dilakukan penulis adalah menyepakati
dan menetapkan bersama bahwa mendongeng merupakan jejaring muatan mata
pelajaran Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya Daerah (PLSBD). Mendongeng
memiliki standar kompetensi khusus dalam mata pelajaran tersebut. Proses pelaksanaannya
dilakukan dengan menyisipkan kegiatan bercerita pada akhir sesi pembelajaran.
Lebih lanjut, ditentukan hari saat kegiatan itu
dilakukan. Bercerita dilakukan dengan membaca buku yang sudah disiapkan atau dengan
alternatif lain, yakni memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bercerita.
Peserta didik mengambil peran aktif karena dalam kegiatan ini mereka tidak
hanya menjadi penyimak. Mereka lebih didorong menjadi pencerita.
Desain selanjutnya, peserta didik menulis satu
contoh dongeng dan kemudian menceritakannya kepada yang lain. Kegiatan ini
dilakukan dengan melibatkan orang tua dalam proses menggali cerita-cerita
rakyat yang secara lisan masih bertahan di lingkungan tempat tinggal (beo). Penulis yakin bahwa banyak cerita
yang masih ‘tersembunyi’ dan perlu ada orang yang mencarinya.
Pelibatan orang tua menjadi bagian penting sebagai
wujud praksis kolaborasi pendidikan. Orang tua membantu peserta didik untuk menyusun
cerita lisan dan dituangkan dalam bentuk tulisan bahasa daerah yang tepat. Proses
ini membutuhkan skenario tenggat penyusunan yang disepakati. Dalam rentang
waktu tersebut, penulis bertugas memfasilitasi proses penulisan dongeng.
Artinya penulis berkewajiban memantau seluruh tulisan yang dibuat melalui
koreksi alur, konfirmasi isi, dan latihan mendongeng cerita.
Agar menjadi lebih efektif, proses fasilitasi dibagi
dalam dua kelompok besar berdasarkan asal kampung. Hal ini dilakukan agar
cerita menjadi produk pembelajaran budaya yang baik, memiliki makna atau nilai,
serta berasal dari sumber yang jelas.
Pada tahap akhir, hasil kegiatan cerita ini ditunjukan
sesi mendongeng. Mendongeng dilakukan dengan konsep kultur Manggarai, sehingga
beberapa hal yang berkaitan dengan itu disepakati, misalnya kostum atau pakaian
yang dikenakan, desain dan etika presentasi. Ketekunan dalam menyelesaikan berbagai
unsur kegiatan cerita mampu ditunjukan oleh setiap peserta didik. Terlihat
bahwa saat mendongeng mereka mampu menunjukkan beragam potensi yang dimiliki.
Selanjutnya, penilaian atas kegiatan ini dilakukan
pada setiap langkah yang meliputi tahap persiapan, proses pengerjaan dan
pelaporan dengan beberapa subunsur di dalamnya. Penulis lebih memilih penilaian
kualitatif dan menulis catatan-catatan (jurnal) tentang perkembangan yang
ditunjukan oleh peserta didik dalam menyelesaikan kegiatannya.
Hal tersebut dilakukan mengingat tujuan awal dari
kegiatan ini adalah literasi budaya. Artinya peserta didik difasilitasi untuk
memiliki kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan daerah
sebagai bagian dari upaya memperkokoh identitasi kebudayaan Indonesia.
Kegiatan berkonteks literasi
seperti ini mendorong peserta didik untuk peduli pada identitas budaya karena peserta
didik memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertutur tentang budaya. Kepedulian
pada budaya menjadi kecambah bagi tumbuhnya ‘pohon’ literasi budaya yang kuat.
Dapat dibayangkan, bila bentuk-bentuk entitas budaya
seperti nunduk tidak dijaga, maka
pengikisan eksistensi pada generasi milenial tidak terbendung. Lantas, apa yang
akan dibanggakan dari generasi berlabel Manggarai. Oleh karena itu, mendukung
gerakan literasi untuk mengakar secara menyeluruh sekolah perlu menjadi jembatan
yang menjaga kesinambungan hidupnya budaya dan proses pendidikan.
Tentu tidak hanya bertumpu pada unsur dongeng saja,
apalagi kecenderungan untuk memprioritaskan satu unsur budaya. Untuk sebuah
dinamika proses pendidikan yang berkarakter, semua unsur dalam paradigma budaya
perlu digali. Gerakan literasi merupakan aktivitas partisipatif yang melibatkan
banyak orang, sehingga untuk menggali lebih dalam tentang budaya, sekolah sebaiknya
berkolaborasi secara intens dengan orang tua, komunitas adat, dan stakeholder
lainnya. Sekolah bisa menjaga identitas budaya.
Editor : Takim/MDj (red)








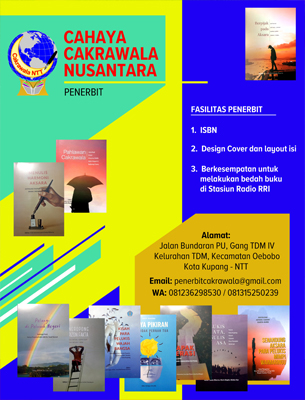










0 Comments