(Sebuah Catatan Reflektif Pada Buku “Jangan Menghina Guruku Lagi” Karya Gusty Rikarno)
 |
| Foto: R. Fahik/ Cakrawala NTT |
Oleh Mario Djegho
Alumnus Undana Kupang, Jurnalis Cakrawala NTT,
Anggota Komunitas Secangkir Kopi (KSK) Kupang
Melukis adalah sebuah kegiatan seni rupa dua dimensi. Kesenian tersebut diwujudkan dalam bidang lukis seperti kanvas dan diekspresikan melalui media garis dan warna oleh seorang pelukis. Seorang pelukis harus memiliki imajinasi, pemikiran, dan konsep secara estetis untuk menimbulkan rasa dan corak kehidupan di dalam lukisannya. Sebagai sebuah karya seni, lukisan bisa berdaya kreatif bagi peminat dan penikmatnya untuk menciptakan sesuatu dalam kaitannya dengan simetrisitas sosial (hubungan antar-sesama dan dirinya sendiri).
Salah satu
pelukis terkenal asal Italia, Leonardo Da Vinci telah membuktikan kuatnya daya
kreasi sebuah lukisan dalam perjalanan hidupnya. Pelukis asli pada karya “Manusia Vitruvian”, “Perjamuan Terakhir” dan “Mona Lisa” tersebut telah membuat cahaya
terang di tengah era Renaissance Italia
lewat ide dan karya seninya, sehingga ia kemudian di kenal sebagai “Manusia Renaissance”. Dalam
pandangannya, seorang pelukis sejatinya memiliki seluruh alam semesta di
pikiran dan tangannya. Hal tersebut akan mendorong seorang pelukis untuk terus
belajar sebagai satu-satunya hal yang tidak pernah dilupakan, tidak pernah
ditakuti, dan tidak pernah disesali oleh pikiran. Oleh karena itu, baginya,
dalam kaitannya dengan seni melukis, kebijaksanaan adalah anak dari
pengalaman.
Proses dan
daya kreasi tersebut juga erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Ibarat sebuah
lukisan, dunia pendidikan pun dilukis oleh para pelukis handal dengan ide,
pemikiran, konsep, dan imajinasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya
visioner itu bertujuan untuk menumbuhkan asa dan rasa pada wajah bangsa secara
edukatif. Lalu, siapakah para pelukis visioner tersebut? Dan tentu jawabannya
merujuk pada sosok guru sebagai tenaga pendidik. Guru adalah seniman terbaik
dalam melukis wajah pendidikan yang akan membentuk wajah bangsa di kemudian
hari. Di dalam diri seorang gurulah segala upaya dan daya kreasi dituangkan
untuk membina, mendidik, dan membentuk pribadi-pribadi baru dalam membangun
simetrisitas dan peradaban sosial yang baik. Tanpa tarikan estetis dari tangan
seorang guru, lukisan wajah pendidikan kita akan terkesan pudar, nihil nilai,
dan terasa hambar.
Sekilas “Jangan Menghina Guruku Lagi”
Realitas
wajah pendidikan dan eksistensi guru di dalamnya juga tergambar jelas dalam pemikiran
Gusty Rikarno
lewat bukunya “Jangan Menghina Guruku
Lagi”. Di dalam buku tersebut, ia mencoba merangkum, menggali, dan mengkaji
data pendidikan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan ramuan cerita yang
sederhana tetapi menarik untuk dicermati. Ia memandang pendidikan sebagai
sebuah sistem besar, dimana semua unsur yang tergabung di dalamnya saling
berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Namun, unsur utama yang menjadi
perhatiannya adalah eksistensi guru sebagai penggerak pendidikan. Baginya, guru
adalah role model yang menjadi
panutan hidup para peserta didik dalam mendalami dan mengimplentasikan semua
ilmu dan pengetahuan dalam setiap proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM).
Dalam
definisinya, terminologi pendidikan diadopsi dari kata Yunani “paedagogie” yang berarti pendidikan dan
“paedagogia” yang berarti bermain
dengan anak. Di sisi lain, pendidikan juga selalu digunakan oleh bangsa Roma
dengan istilah “educare” dan bangsa
Jerman dengan istilah “erziehung”
yang sama-sama berarti mengeluarkan dan menuntun. Ketiga istilah yang diadopsi
oleh terminologi pendidikan sejatinya berarti mengeluarkan atau mengeksplorasi
potensi positif-produktif individu dan menuntunnya dalam bidang peminatan yang
sesuai secara potensial menuju sesuatu yang berguna dan bersifat konstruktif.
Dengan demikian, pendidikan merupakan wadah pembangunan manusia dalam konteks
perubahan yang lebih baik. Di dalam wadah itulah peran guru menjadi sosok
penting yang membentuk dan menuntun setiap individu sesuai potensi dan arah
pergerakannya di kemudian hari.
Hal tersebut
senada dengan pandangan Syah (2011) dalam bukunya “Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Terbaru” yang mengartikan
pendidikan sebagai sebuah proses dimana individu-individu tertentu memperoleh
pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhannya
dengan metode-metode tertentu. Dalam proses itulah peran guru menjadi semakin
konkret ketika pengaktualisasian metode-metode pendidikan membutuhkan
figur-figur profesional dalam bidang pendidikan.
Buku “Jangan Menghina Guruku Lagi” karya Gusty Rikarno secara jelas menggambarkan
realitas guru dan wajah pendidikan di lingkup NTT. Ia menuliskan semua
pengalaman pribadinya tentang dinamika pendidikan berserta dampak yang turut
diboncenginya. Sekali peristiwa, ia mengisahkan dan menggambarkan situasi
keresahan para pemangku kebijakan, guru, dan semua pelaku pendidikan akibat
rendahnya hasil Ujian Nasional di Provinsi NTT dalam rerata nasional. Tentunya,
keresahan itu membuatnya harus mencari segala celah kosong demi melihat secara
lebih mendalam penyebab rendahnya kualitas pendidikan di NTT.
Di lain
kesempatan, ia juga mengisahkan tentang kualitas guru sebagai tenaga pendidik
di NTT. Rendahnya kompetensi dan minimnya budaya literasi di lingkungan tenaga
pendidik juga menjadi batu sandungan bagi percepatan pembangunan manusia (human development) di NTT. Di sisi lain, yang lebih menyita
perhatian adalah ketika ia menggambarkan bagaimana para pelajar dan mahasiswa
rela “menjajakan diri” dalam “wisata seks bebas” demi menunjang gaya hidup (life style) ataupun demi sesuap nasi.
Mirisnya lagi, dalam penelitian sederhananya, ia menemukan bahwa masyarakat
lebih cenderung memuaskan dahaga “isi perut” ketimbang kebutuhan “isi kepala”.
Semua terkemas rapi dalam buku “Jangan
Menghina Guruku Lagi” ini.
Proses
pembahasan yang sederhana dengan uraian cerita yang menarik membuat buku ini
bisa dibaca oleh semua kalangan. Namun, buku “Jangan Menghina Guruku Lagi” ini sebenarnya ingin menggambarkan
secara holistik bagaimana realitas pendidikan di NTT sambil menawarkan solusi
sesuai kebutuhan zaman.
Wajah Guru Sebagai Pelukis Wajah Bangsa
Seperti
halnya Leonardo Da Vinci, guru sebagai pelukis wajah bangsa melalui dunia
pendidikan harus mampu menghidupkan karyanya dengan baik. Dengan kata lain,
esensi dan dan eksistensi guru dalam dunia pendidikan harus diperhatikan secara
serius. Jika di dalam buku “Jangan
Menghina Guruku Lagi” seorang Gusty
Rikarno sangat intens memperhatikan kualitas guru dan pendidikan, maka sudah
saatnya wajah guru sebagai seorang pelukis dilukis ulang demi terjaganya
dinamika pendidikan yang lebih bermartabat. Lalu, siapa yang harus melukis
ulang wajah para guru?
Sebelum
menjawab pertanyaan tersebut, esensi dan eksistensi guru harus diuraikan
terlebih dahulu dalam kerangka kompetensi. Standar dan kualitas guru secara
personal pada dasarnya diukur dalam tataran kompetensi. Kompetensi tersebut
menjadi suatu tanda pendeskripsian kecakapan, kemampuan, dan integritasnya
sebagai pendidik profesional dengan beberapa indikator tertentu. Berdasarkan
Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat
(1) menyatakan bahwa “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan
kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”.
Lebih lanjut,
menurut Conny R. Semiawan, ada tiga kriteria utama yang menjadi penunjang
kompetensi seorang guru, yakni knowledge
criteria, performance criteria,
dan product criteria. Yang pertama, Knowledge criteria merupakan kemampuan
intelektual yang dimiliki seorang guru yang meliputi penguasaan materi
pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan mengenai tingkah
laku individu, pengetahuan tentang kemasyarakatan dan pengetahuan umum. Yang
kedua, performance criteria adalah
kemampuan guru yang berkaitan dengan berbagai keterampilan dan perilaku, yang
meliputi keterampilan mengajar, membimbing, menilai, interaksi sosial dan
pergaulan, serta cara berkomunikasi. Dan yang terakhir, product criteria merujuk pada kemampuan guru dalam mengukur
kemampuan dan kemajuan siswa setelah mengikuti proses belajar-mengajar (Danim,
Sudarwan, Kairil, 2015. Profesi
Kependidikan).
Jika
ditelisik lebih jauh, kompetensi guru dan penunjangnya tersebut serupa dengan
pandangan Leonardo Da Vinci bahwa pelukis hebat selalu memiliki semesta dan
pikiran di tangannya, sehingga pengalaman dan proses belajar adalah langkah
utama yang menjadikannya bijaksana. Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab
dalam teori belajar sosial, guru adalah pijakan dan patokan pembelajaran
peserta didik, sehingga seorang guru yang bijak akan menghasilkan begitu banyak
kebijaksanaan dalam diri peserta didik. Kompetensi guru tersebut pada akhirnya
bermuara pada eksistensi dan kedudukan guru yang tidak hanya dipahami sebagai
sebuah profesi pekerjaan, tetapi juga mengemban misi peradaban sebagai tujuan
dari sebuah pendidikan. Oleh karena itu, kompetensi guru menjadi satu bentuk
kombinasi antara kecakapan, kapasitas, kemampuan dan integritas etis guru dalam
perannya sebagai model atau teladan di dalam kelas. Peserta didik akan meniru
dan mengimplementasikan apa yang ditampilkan, diajarkan, dan dikatakan guru
sebagai bagian dari evaluasi dan proses perubahan sikap dan perilaku peserta
didik.
Lalu,
jawaban yang tepat dalam memenuhi pertanyaan “siapakah yang akan melukis ulang wajah guru kita?” adalah guru itu
sendiri. Di dalam buku ”Jangan Menghina
Guruku Lagi” ini, Gusty
Rikarno sekali lagi menggambarkan sosok “kambing hitam” yang selalu dicari
ketika semua pihak terlilit sebuah problema pendidikan yang tidak pernah
menemui jalan keluarnya. “Kambing hitam” tersebut bisa merujuk pada pemerintah,
ketersediaan dana operasional sekolah, hingga kurangnya fasilitas penunjang
fisik. Lalu, ketika “kambing hitam” itu terus berkeliaran tanpa arah,
bagaimanakah nasib masa depan pendidikan kita? Dengan demikian, Gusty Rikarno dengan tegas mengatakan “Bunuh saja kambing hitam itu, jangan dicari
lagi”. Artinya, semua perubahan harus berdasar pada sikap ingin berubah,
bergerak, dan bekerja dengan inisiatif yang inovatif dan produktif. Oleh karena
itu, guru harus bisa menjadi pelukis ulang wajahnya sendiri dengan bercermin
diri, terus belajar, dan terus berupaya di tengah keterbatasan demi mewujudkan
mimpi mencerdaskan kehidupan bangsa.
Literasi : Penuntun Dasar bagi Pelukis
Wajah Bangsa
Sekali
kisah, dalam bukunya “Jangan Menghina
Guruku Lagi” ini, Gusty
Rikarno menceritakan pengalamannya tentang maraknya kasus “perjokian” di dalam
dunia pendidikan. “Perjokian” juga sering terjadi ketika para guru dituntut
untuk menunjukan kualitas tulisannya demi menunjang proses kenaikan pangkat.
Seorang guru yang berkualitas secara kompeten dan cakap secara intelektual akan
mampu mempertanggungjawabkan mutu personalnya. Namun, segelintir guru yang
belum maksimal secara intelektual dan pengalaman akan terjerumus ke dalam kasus
“perjokian”. Artinya, ia akan menggunakan jasa pembuatan tulisan yang dibuat
oleh pihak lain, seperti kasus “perjokian” yang terjadi dalam proses pembuatan
skripsi yang marak di perguruan tinggi.
Kasus
sederhana yang dilukiskan oleh Gusty
Rikarno tersebut sebenarnya ingin menunjukan bahwa sudah saatnya para guru
bergerak maju sambil berbenah diri. Bagaimana caranya? Perkuat budaya literasi
dan tingkatan intensitas kegiatan baca dan tulis di kalangan guru. Dengan
demikian, ketika esensi dan eksistensi guru dipertanyakan, guru mampu
menunjukan kualitas dan kompetensinya secara baik, sehingga sampai kapanpun,
tidak ada lagi yang akan menghina para guru.
Ibarat
melukis pada kanvas, literasi menjadi alat lukis yang dibutuhkan oleh pelukis
dalam mengekspresikan pikiran dan imajinasinya melalui media warna dan garis.
Menurut
Elizabeth Sulzby, seorang professor pendidikan dari University of Michigan yang
menggagas konsep literasi usia dini, literasi adalah kemampuan berbahasa yang
dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi. Kemampuan tersebut terdiri atas
kegiatan membaca, berbicara, menyimak dan menulis. Singkatnya, literasi
berhubungan erat dengan keaksaraan, yaitu kemampuan menulis dan membaca. Oleh
karena itu, hal pertama yang harus dilakukan oleh para guru adalah terus
membaca dan menulis, seperti yang ditulis oleh Gusty Rikarno dalam bukunya ini, yakni
“Jangan pikirkan apa kita tulis, tetapi tulislah apa yang kita pikirkan”.
Literasi
membaca dan menulis adalah pintu gerbang dalam memahami bentuk literasi lain,
seperti lliterasi numerasi, literasi budaya dan keluarga, literasi digital, literasi
finansial, dan literasi sains. Guru harus mampu menceburkan diri di dalam
setiap kegiatan literasi, terutama menyangkut keaksaraan. Seperti yang
ditekankan oleh Leonardo Da Vinci, kebijaksanaan adalah anak dari pengalaman,
guru juga harus menambah kualitas diri dengan menggenggam banyak pengalaman
dalam proses belajar yang berkelanjutan.
Pada
akhirnya, melalui budaya literasi yang baik, lukisan wajah para guru akan
terlihat menarik, dan tentunya wajah pendidikan pun bisa terlukis ulang secara
baik pula. Melalui buku “Jangan Menghina
Guruku Lagi” karya Gusty
Rikarno ini, semua pihak dipacu untuk bisa memahami pendidikan secara
menyeluruh, terutama guru sebagai unsur penting di dalamnya. Guru adalah sosok
penting dalam proses pendidikan, sehingga mutu dan kualitas seorang guru juga
harus terjaga secara baik.
Hal
tersebut (mungkin) berguna dalam merealisasikan filsafat pendidikan Ki Hajar
Dewantara dan Driyarkara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus
menekankan penguatan nilai-nilai luhur bangsa sendiri agar tidak kehilangan
jati dirinya, sedangkan bagi Driyarkara, pendidikan harus mengajarkan setiap
individu untuk memahami dan menyadari keberadaannya yang turut mempengaruhi
lingkungannya. Oleh karena itu, pendidikan dirancang tidak hanya sebatas untuk
memenuhi kebutuhan pragmatis ekonomi dan profesi, tetapi lebih jauh menyangkut
humanisasi. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, seperti halnya
melukis, semua pihak yang terlibat di dalamnya harus mampu berupaya dan berdaya
kreatif.
Editor: R. Fahik/ red






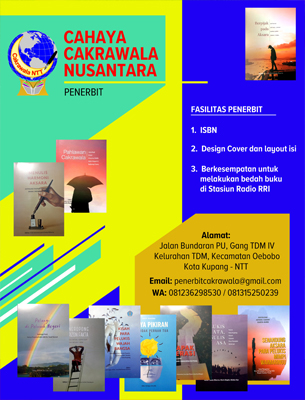










0 Comments