Oleh: Marselus Robot
Dosen Bahasa dan Sastra
FKIP Undana
Marcelrob32@gmail.com
Memandang perempuan dalam kepustakaan apapun atau dalam
budaya manapun selalu terpendar
dalam liur-liur libido kelaki-lakian. Topik perempuan begitu
balepotan dengan melankolisme yang
terkadang membuat kalap. Semakin banyak sisi yang diperbicangkan, bahkan dicincangkan, semakin
banyak pula yang ditinggalkan dan terus saja mengendap di sisi lorong sejarah
kebudayaan manusia. Mungkin pula karena
penampakan perempuan lebih bersifat
teka-teki dari pada laki-laki. Walau begitu, toh, perempuan tetap saja mengambil posisi sebagai
oase di tengah kesangaran laki-laki, perempuan menjadi bejana yang meneteskan
anggur keselamatan di piala kehidupan, sampai
desah napasnya begitu merdu menyapu rindu.
Persoalan yang
kemudian dirundung pelit dan sulit, ketika memandang perempuan dari mata laki-laki yang tak jeli
dan tak pernah selesai. Padahal, perbedaan lelaki dan perempuan bukan sekadar gender dalam pengertian jenis
kelamin. Semestinya, membicarakan perempuan bukan karena dia perempuan, melainkan
karena dia bukan laki-laki.Sebab, apa yang
diberikan perempuan kepada kehidupan tidak seperti yang diberikan oleh
laki-laki. Di sanalah sosok perempuan
demikian perkasa dalam kelembutannya. Ia berbicara banyak dengan diamnya. Ia begitu
setia menjulurkan payudaranya untuk menyususui kehidupan dan membentangkan cadar
peradaban bagi manusia. Itulah sebabnya, perempuan selalu hidup dalam mitos
atau dimitoskan. Sudjiwo Tedjo pernah berkata, “Saya tidak pernah
tahu wajah perempuan itu seperti apa. Saya cuma bisa membayangkan betapa
tabahnya perempuan itu. Sebagaimana kalau saya bayangkan legenda maupun mitos
tentang para inang di banyak daerah.”
Lantas bagaimana
perempuan yang hidup dan dihidupkan oleh
orang Lamaholot (Flores Timur) dalam mitos-mitos? Dengan pertanyaan yang lebih
akrab, siapakah perempuan dalam mitos orang Lamaholot, Mikhael Boro Bebe berusaha sekuat lengan pikirannya menghela
perempuan dari lipatan mitos orang Lamaholot. Mikhael begitu suntuk mencangkul makna
di balik metafora yang hidup dalam kisah-kisah suci tentang perempuan
Lamaholot. Sebagai “orang dalam” (the
insider), Mikhael Boro Bebe sangat terlibat dalam kebudayaan Lamaholot. Kualitas
keterlibatannya justru ketika dia mampu menghela butir-butir mutiara di balik lipatan
mitos tentang perempuan Lamaholot.
Membaca buku ini seakan saya bertemu dengan perempuan Lamaholot dalam definisi yang lain. Sosok istimewa bukan karena ia perempuan, melainkan lebih-lebih karena ia bukan laki-laki. Sosok mulia karena rela mengorbankan dirinya demi menghidupkan persaudaraan. Ia memberikan hidup melalui kematiannya. Darah, daging, dengan rela diserahkan untuk dikurbankan bagi orang lain. Ia adalah sosok penuh epik bukan untuk diintip, melainkan dimaknai dalam konteks kehidupan orang Lamaholot. Karena itu, orang Lamaholot menyebut perempuan dengan metofora (perumpamaan) yang begitu efimis (halus) dan feminisuntuk mengawetkan citra kemuliaan dan keagungan perempuan.
Orang Lamaholot
memuliakan perempuan sebagai sang yang menghadirkan kehidupan, atau Ibu
Kehidupan. Suatu metafora yang amat luas, seluas kehidupan
itu sendiri. Semisal, sapaan Ina Tana Ekan sebagai pasangan Ama Lera Wulan, sebuah metafora yang merujuk pada Ibu Bumi atau Ibu Kehidupan (sumber kehidupan), termasuk tatanan
peradabannya. Dalam citra seperti itu, ibu sebagai bagian dari semesta
kosmogoni orang Lamaholot, mulia dan diagungkan. Milkhael Boro Bebe mencontohkan sebutan “Ina
kayo puken-bine wai matan” yang berarti ibu pangkal pohon dan sumber mata air.
Pola arkais ini mengartikan bahwa ibu adalah asal, pokok, pangkal, dan sumber
air kehidupan. Dalam bacaan semiotis,airsebagai
tanda,sebagai penawar dahaga, menyegarkan (membahagiakan) dan potensi kehidupan.
Ambil satu contoh mitos yang dalam buku ini dikaji secara
khusus ialah Tonu Wujo. Dalam mitos ini, perempuan dicitrakan sebagai orang yangrela menyerahkan diri untuk
dikurbankan (dibunuh) demi kehidupan saudaranya.Mitos
Tonu Wujo merupakan asal-mula padi. Mirip
dengan mitos masyur versi Jawa tentang Dewi Sri (asal-usul padi). Tonu Wujo
menjelma menjadi padi. Dikisahkan, Tuno
Wujo menyerahkan lehernya disembeli, tubuhnya dipotong-potong,
darah dan dagingnya ditaburkan di atas kebun milik saudaranya. Ia mati untuk
menghidupakn. Rela berkorban untuk orang lain. Hidup berarti rela berkorban untuk sesama.
Sebelum ia menyerahkan diri untuk dibunuh, Tonu Wujo bertitah sendu: “Na’a
go’e pake dike, aman go’e salen sare, gute nala suri sina, pile nala kada jawa,
kote nope lega tapo, ebu nope dekan muko” (“saudaraku telah memakaikan-mengenakan
pakaian elok, maka ambilah parang Cina, raihlah pedang Jawa, penggallah
kepalaku bagai membelah satu buah kelapa, tikamlah perutku seperti tandan
pisang”). Betapa melodramatis, perempuan Tonu Wujo begitu rela
dirinya untuk dibunuh demi kehidupan saudaranya.
Setidaknya ada tiga
keping hostia sebagai pesan yang ditinggalkan Tonu Wujo. Pertama, Ia rela
berkurban untuk suatu kehidupan. Itu berarti pula bahwa mengeksistensi di dunia adalah dengan menempuh jalan pengurbanan bagi sesama. Kedua,
mitos ini meminta kita untuk melihat perempuan sebagai sumber kehidupan. Ia
menjelma menjadi padi sebagai sumber kehidupan. Tuno Wujo perempuan yang menggemakan suara profetis (seakan terdesah suara
bunda atau kenabian) dari lipatan mitos itu. Perawan tak ternoda yang menolak
untuk menikah dan lebih memilih menjadi kurban untuk Lera Wulan Tana Ekan demi kehidupan dan kasih sayang terhadap
saudaranya. Ketiga, Tonu Wujo pewaris kebajikan bagi sesama. Persaudaraan dan
kebersamaan jauh lebih penting dari sekadar hewan atau harta benda. Ia menolak hewan, gading, mahar lainnya ketika saudaranya
menyuruhnya untuk menikah. Bagi Tonu Wujo, harta benda tidak akan cukup. Yang
mencukupkan hidup adalah usaha membagi dan rela berkorban. Hasrat bendawi bukan
saja membuat manusia kesurupan dan kehilangan kepekaan kemanusiaan, tetapi manusia
kadang senilai dengan benda. Tak bermartabat.
Citra perempuan yang berkorban demi kehidupan tidak
hanya dijumpai dalam kisah Tuno Wujo, tetapi juga Nogo. Nogo yang dalam mitos Lamaholot
disebut Bala Nago adalah seorang jelita (gadis) yang direguk laut. Mikael Boro Bele mengutip ceritera itu sebagai berikut:
Nogo
merupakan perempuan periang, lincah, dan rajin bekerja membantu ibunya. Ia
pekerja keras. Pekerjaan yang suka dilaksanakan adalah mencari siput dan
menangkap ikan di laut. Nogo mengalami peristiwa naas yakni dihempas ombak dan
menghanyutkannya ke tengah laut. Peristiwa naas ini menyelimuti duka yang
mendalam bagi ibunya. Saban hari ibu dengan tabah dan sabar mencari anaknya.
Sebagai gantinya, ibunya mendapat gading sebagai belis dari pangeran penghuni
laut. Gading itu merupakan jelmaan dari ranting kering yang dipungut di pantai.
Masyarakat Lamahelan, Adonara mengenal kisah ini dengan istilah Bala Nogo
(gading Nogo).
Laut dan Lamaholot adalah setali mata koin. Laut adalah
ladang-ladang mata pencaharian. Ceritera rakyat, lagu,
dan liuk tarian mengambil watak laut. Bala Nogo adalah Si Jelita dalam ceritera Lamaholot adalah
perempuan yang diculik Pangeran Penghuni Laut. Pangeran Laut
telah memberikan mahar gading kepada Ibunda Nogo. Hingga saat ini, mahar mahal
dan penting dalam tradisi perkawinan orang Lamaholot adalah gading. Nilai atau
mahar gading demikian penting bukan karena kualitas ganding, namunkisah pengorbanan
Nago di balik gading itu. Itulah sebabnyaorang Lamaholot
memuliakan dan mengagungkan perempuan sebagai sumber kehidupan.
Spirit pengorbanan itu terlacak pula dalam legenda Wai Leto Matan. Menurut Mikhael Boro Bebe, legenda ini mengisahkan pengorbanan seorang perempuan Tonu Uto Wata Wuyo Hadun Horet (Uto Wata), versi lain “Sabu Peni” yang menikah dengan Kopong SedeLewo Lein Mamun Liko Lewo Weran
(Kopong Sede) makhluk gaib penguasa air. Sumber air ini menjadi mas kawin bagi Uto Wata. Dari sumber air tersebut
muncul pula gading jelmaan dari batang kayu, kalung emas jelmaan tali, emas
berkepala penyu jelmaan ranting daun, dan anting jelmaan buah pohon. Harta
warisan ini dijaga suku Lewo Lein dan
disimpan di korke (rumah adat) desa
Lewokluok. Peristiwa ini terjadi di Lewokluo
Woyon Tobo-Tana Knilok Nape Hape (desa Lewokluok) kampung yang sealu
menyimpan persediaan makanan dan Lewo
Blepa Lolon Girek-Tana Hala Lolon Burak (desa Blepanawa).
Kisah Wai Leto Matan mirip dengan Tonu Wujo yang
memperlihatkan sikap rela berkorban
untuk sesama. Pengorbanan tidak dimbali dengan barang atau jasa apapun,
kecuali menghargai dan memuliakan
perempuan sebagai ibu kehidupan yang
telah memberikan jiwa raganya kepada sesama. Dalam bacaan saya, buku ini dipandang cukup lengkap.
Mikhael Boro Bebe mengadministrasikan
konsep-konsepnya dengan apik, sehingga orang dapat membaca isi keseluruhan buku
ini. Mikhael membuka buku
ini dengan menguraikan hakekat mitos. Ia menggelar secara luas konsep-konsep
mitos (Bab I). Disusul dengan usaha menyingkap perempuan Lamaholot dalam Mitos Tuno Wujo (Bab II). Perjalanan Mikhael Boro Bebesampai
pada usaha menguak perempuan Lamaholot dalam
ceritera rakyat
Lamaholot. Seperti siapa perempuan dalam ceritera rakyat Lamaholot diungkap secara lugas dan tuntas. Perjalanan
pencarian makna perempuan dalam mitos dan ceritera rakyat yang dilakukan
Mikhael Boro Bebe sampai pada mengkaji relevansi
mitos dan ceritera rakyat terhadap realitas perempuan
Lamaholot. Mikhael Boro melihat semacam kelainan sosial. Misalnya, pada satu
sisi, terutama dalam mitos, perempuan begitu diagungkan, ditampilkan dengan
citra yang penuh spirit pengorbanan, damai dan kasih yang ditinggalkan. Ia rela
menyerahkan diri untuk kehidupan orang lain. Pada pihak lain, keadaaan ini
berbeda dengan realitas sosial atau pengalaman empirik orang Lamaholot. Perempuan tidak
dihormati sebagai kisah-kisah dalam mitos dan ceritera orang Lamaholot.
Sedangkan realitas perempuan hanya sebagai suku
cadang perkakas dapur. Bahkan perempuan menjadi budak belian di tanah rantau. Martabatnyadiciutkanmenjadi
barang yang diperdagangkan. Inilah ruang refleksi yang disedikan oleh Mikhael
Boro untuk tidak segera baleNagi,
tetapi kembali ke pangkuan Ine Ata Puken,
Ibu Kehidupan yang telah menyerahkan dirinya dengan rela demi kehidupan “Ata Lamaholot”.
Sambil menyulih mitos-mitos itu dalam bentuk teks (buku)
ini, Mikhael Boro Bele menginterpretasi untuk
menghela makna yang terkandung di dalamnya. Di sanalah pembaca sungguh dijamu
oleh Mikhael Boro Bebe. Sebab, Mikhael Boro memberikan semacam eksegese yang
cukup memadai sehingga pembaca dapat mencicipi langsung makna yang tersaji
dalam mitos-mitos tersebut. Akan tetapi, penulis buku yang baik selalu
menyediakan ruang tamu bagi pembaca untuk “ngobrol” (memberikan saran dan
kritik), sehingga buku ini hidup dalam pikiran pembaca.
Selamat membaca
dan dekaplah perempuan Lamaholot dengan penuh kemuliaan. Jangan biarkan sukacita menguap
dari tubuhnya. Sebab, jiwa raganya adalah matahari kebajikan, titahnya adalah
nyanyian yang bermada pada semesta, dan pengorbannya meranumkan kasih sayang. Ine ata Puken, Ibu Kehidupan.


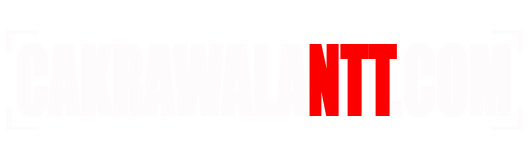
















0 Comments