Redaktur
Cakrawala NTT
Pengantar Redaksi:
Tanggal 23 September diperingati
sebagai Hari Maritim Nasional. Dalam konteks tersebut, redaksi menurunkan tulisan
ini untuk menggugah kesadaran kita akan pentingnya menjaga kedaulatan maritim sebagai
bagian dari semangat nasionalisme dalam bingkai NKRI. Tulisan ini menghantar penulis meraih Juara
III Wilayah Dua Lomba Menulis Artikel Parade Cinta Tanah Air Tingkat Pusat Tahun
2015 (Kementerian Pertahanan RI). Selamat Hari Maritim Nasional Tahun 2020!
Pengantar
Diskusi
tentang kedaulatan bangsa sedikit miris jika melihat banyak realitas miring
dalam konteks sosial Indonesia saat ini. Sebab, sebagai bangsa yang telah ada
sejak dahulu dan negara yang telah merdeka tujuh puluh tahun (tahun 2015, red)
Indonesia mestinya tidak lagi bermasalah dengan banyak hal. Usia tujuh puluh (tahun
2015, red) merupakan usia dewasa bahkan sangat dewasa dalam kategori fisik biologis.
Di usia demikian, Indonesia masih berkutat dengan masalah kemiskinan, rawan
pangan, gizi buruk, masalah pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
Beragam
masalah itu menarik untuk dibahas dan dihubungkan dengan konteks kedaulatan
bangsa kita. Untuk tujuan itu maka tulisan ini membahas satu masalah krusial
terkait dengan pangan. Sebab, sebagai manusia biologis, pembangunan apa pun
bentuk dan modelnya baru dapat berjalan jika perut manusia di dalamnya kenyang.
Tulisan ini dimulai dengan sebuah tesis utama. Kedaulatan bangsa hanya dapat
dipahami sejauh memahami kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan akan tercapai
jika kita mengoptimalkan pemanfaatan SDA laut yang ada di Indonesia. Dengan
demikian, jika bangsa ini tidak lagi terjebak dalam situasi rawan pangan maka
bangsa Indonesia akan berdaulat.
Konteks Indonesia
Menteri
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (BDPTT) Marwan Jafar mengungkap, hingga saat ini masih terdapat 57 kabupaten dari total
508 kabupaten/kota di Indonesia yang masuk kategori rawan pangan. Daerah rawan
pangan ini hampir menyebar di seluruh wilayah di Indonesia yakni sebagian besar di
Papua, dan Nusa Tenggara Timur serta sebagiannya menyebar di Nusa Tenggara Barat, Sumatera, Kalimantan,
dan Jawa. Luasnya penyebaran daerah rawan pangan ini merupakan situasi kronis
dimana semua elemen masyarakat dituntut
untuk bergandengan tangan memerangi dan melenyapkan bahaya rawan pangan.
Dalam UU/No 7/Tahun 1996 dan disempurnakan
menjadi UU/No 68/Tahun 2002 tentang ketahanan pangan dijelaskan bahwa: “Ketahanan
Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari
tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan
terjangkau. Sedangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber
hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan,
bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan,
pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman”.
Persoalannya adalah bahwa di Indonesia
pangan identik dengan darat dan pertanian. Pangan dimengerti sejauh memahami
pertanian. Padahal, laut memiliki biota yang menyokong dan mendukung ketahanan
pangan. Berdasarkan penelitian LIPI yang di lakukan di perairan
laut dalam Selatan Jawa dan Barat Sumatera, terungkap bahwa setidaknya terdapat
529 jenis biota yang
berpotensi untuk mendukung ketahanan pangan melalui diversifikasi produk
pangan. Masing-masing 415 termasuk dalam jenis ikan, 68 jenis udang dan
kepiting, serta 46 lainnya adalah jenis cumi-cumi.
Indonesia juga memiliki sekitar 13 dari 20 spesies lamun
dunia, 682 spesies rumput laut, 2.500 spesies moluska, 1.502 spesies krustasea, serta 745 spesies
ekinodermata. Potensi sumber daya kelautan tersebut berpeluang untuk
menghasilkan devisa negara jika dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan. Karena laut kita memiliki luas wilayah 75%
teritorial laut (5,8 juta km2) lebih besar jika dibandingkan dengan wilayah
daratan. Dan jika seluruh potensi kelautan ini dikelola
dengan baik maka diperkirakan 85% perekonomian nasional bakal sangat bergantung
pada sumber daya kelautan termasuk pangan. Pembangunan Politik pangan
kelautan yang pro rakyat harus diaplikasikan dalam menjamin kecukupan kebutuhan
pangan setiap individu secara merata,
serta mampu mengentaskan pengangguran dan kemiskinan yang ada di Indonesia.
Revolusi Biru
Rawan
Pangan bukanlah suatu persoalan yang baru. Masalah ini sudah ramai
diperbincangkan dunia sejak beberapa tahun silam. Kekhawatiran terhadap pangan
telah ada dalam sejarah. Sejak 10 ribu
tahun yang lalu di Tiongkok sudah
mengenal lumbung untuk menyimpan makanan hingga saat musim lapar tiba. Istilah
rawan pangan (food security)
merupakan kondisi menurunya ketahanan pangan dalam masyarakat,
baik yang sifatnya kronis (chronical food
insecurity) maupun yang bersifat sementara (transitory food insecurity). Rawan pangan kronis merupakan situasi
di mana kepemilikan pangan lebih sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan
akan pangan tersebut dan terjadi sepanjang
waktu. Sedangkan rawan pangan sementara merupakan kondisi rawan pangan
yang terjadi musiman. Meskipun sementara, rawan pangan seperti ini bersifat
akut. Akut karena rawan pangan ini terjadi karena adanya kekeringan atau musibah lainnya yang menyebabkan
masyarakat mengalami kekurangan pasokan akan
pangan.
Revolusi hijau (green revolution) adalah
pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi tanaman pangan,
terutama tanaman serealia, (bahan makanan pokok seperti gandum, jagung, padi,
kentang, sagu). Jadi tujuan dari revolusi hijau ini adalah untuk mencukupi tanaman pangan
penduduk. Tujuan tersebut tentunya berawal dari
mitos bahwa beras adalah komoditas strategis baik ditinjau dari segi ekonomi,
politik, budaya dan sosial.
Namun oleh karena penyeragaman pangan ke
beras maka menimbulkan dampak negatif yaitu terpeliharanya paradigma kita yang selalu beranggapan bahwa pangan
hanya kita peroleh sejauh kita mengolah lahan daratan dengan baik. Padahal Indonesia
merupakan tanah air, yang berarti bahwa Indonesia tidak hanya terdiri dari
tanah tetapi juga air yang memiliki luas 3 kali lipat lebih luas dari daratan. Sementara
di lain pihak pertumbuhan penduduk
semakin meningkat dari tahun ketahun, konversi lahan menjadi pemukiman penduduk
serta berdirinya bangunan-bangunan megah terus terjadi, belum lagi kekeringan
yang terjadi dimana-mana merupakan faktor penyebab gagalnya revolusi hijau
tersebut.
Padahal, dengan mengolah sumber daya air khususnya lautan di Indonesia
secara optimal, saya yakin Indonesia akan menjadi negera maritim yang besar dan
mandiri. Wacana tentang rawan pangan bagi Indonesia merupakan suatu yang sangat
mustahil terjadi jika kita memanfaatkan sumber daya kelautan
secara maksimal. Penganekaragaman
pangan ini membutuhkan perubahan paradigma soal makanan sehat. Makan beras
ternyata dapat memicu penyakit diabetes dan Indonesia adalah negara dengan
penderita diabetes terbanyak keempat di dunia. Oleh karena itu, pembangunan
kelautan menjadi sangat strategis bila dikaitkan dengan ketahanan pangan dan
nutrisi. Sebab, di masa yang akan datang, laut merupakan kontributor terpenting
bagi ketahanan dan kemandirian pangan Indonesia.
Selama ini banyak orang beranggapan, laut hanya
menyediakan sumber protein. Sebetulnya laut menyediakn lebih banyak dari itu.
Laut bukan hanya menyediakan sumber protein, tapi juga kebutuhan sumber-sumber
makanan lainnya, seperti karbohidrat, vitamin dan mineral. Berangakat dari persoalan diatas,
hemat saya sudah saatnya kita harus fokus
kerevolusi biru (The Blue
Revolution) bila kita ingin mencapai kedaulatan pangan. Karena itu
pembangunan budaya kelautan harus dilaksanakan secara komperhensif pada semua
bidang kehidupan kita.
Arah Kebijakan Pangan Laut
Untuk mencapai
kedaulatan pangan laut, maka berbagai upaya perlu dilakukan baik dari tingkat
pusat hingga daerah. Yaitu yang pertama, mendorong pemerintah agar mengubah paradigma sumber pangan dari orientasi daratan
ke arah lautan sebagai sumber pangan alternatif. Secara bertahap dan
pasti industri bioteknologi pangan kelautan harus dibangun di setiap daerah pesisir lautan yang memiliki
potensi produksi perikanan melimpah seperti di Indonesia kawasan timur, dan
daerah kelautan terluar lainnya. Dengan
begitu, maka pemerataan pembangunan di Indonesia bisa tercapai.
Kedua
mengurangi bahkan menghapus impor bahan pangan yang bersumber dari kelautan.
Indonesia harus belajar untuk mandiri. Karena itu perlu adanya gerakan cinta
produk lokal. Ketiga, menjadikan sektor
kelautan menjadi sumber kekuatan ekonomi nasional. Saatnya pembangunan nasional melebar ke kawasan pesisir.
Permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat pesisir mutlak
diperhatikan. Pembangunan SDM,
infrastruktur, penguatan diplomasi
serta pertahanan di daerah pesisir
lautan harus dibenahi menjadi lebih baik.
Keempat, perlu adanya penanaman nilai bahari pada masyarakat khususnya bagi
kaum muda sebagai generasi penerus, baik melalui pembentukan kurikulum
berbasis maritim,
sosialisasi, pelatihan serta meningkatkan
anggaran dan penelitian pangan laut. Adanya riset penelitian di bidang pangan kelautan, akan
menumbuhkembangkan inovasi dan daya saing produk. Identifikasi komoditas pangan
kelautan yang menjadi unggulan di setiap kabupaten/kota pesisir perlu dikembangkan
sebagai kompetensi inti industri suatu daerah sehingga dapat terwujud satu desa
satu produk unggulan pangan kelautan yang bernilai tambah. Pada akhirnya akan
berkontribusi terhadap perekonomian regional secara umum. Dan juga mendorong
pemerintah dalam melindungi dan menyejahterakan nelayan sebagai pelaku usaha
pangan. Penanganan hasil tangkapan laut oleh nelayan perlu di benahi agar
kualitasnya bagus dan harga tidak dimonopoli tengkulak.
Dan yang tak kalah pentingnya adalah
melibatkan kaum muda dalam membangun kemaritiman. Pembangunan yang baik adalah pembangunan
yang berkelanjutan. Maka untuk
itu kaum muda harus berperan penting
disana. kaum muda harus menjadi agent utama dalam membangun laut dan kelautan.
Pemikiran kritis untuk menjadikan laut sebagai basis pembangunan
menjadi tugas yang
harus dikerjakan kaum muda. Kaum muda juga harus mampu memainkan perannya sebagai pengontrol pemerintah dalam
berbagai kebijakan. Karena sebentar lagi tongkat estafet Negara Indonesia
akan jatuh di pundak kaum muda.
Dengan berbagai upaya diatas, diharapkan
laut menjadi sektor primer bagi Indonesia. Karena itu berbagai peraturan
tentang laut dan pangan laut perlu ditegaskan. Masyarakat Indonesia juga harus
mampu menempatkan laut sebagai mata pencaharian utama,karena jika dikelola
dengan baik dan bijaksana, laut dapat membuka 40 juta lapangan kerja bagi
masyarakat.sehingga berbagai masalah sosial baik kemiiskinan, pengangguran, human trafficking, TKI, utang luar
negeri bisa dihapus.
Dan pangan
dari sektor kelautan dapat diterapkan dalam masyarakat dan kedaulatan
pangan dapat tercapai. Pangan laut harus menjadi makanan pokok Negara kita,
saya sangat berharap agar ke depannya masyarakat dapat mengkonsumsi pangan dari
laut yang kaya akan nutrisi. Sehingga mampu melahirkan generasi yang cerdas dan
unggul di mata dunia. Mari kita bangun budaya maritim kita menuju kedaulatan
bangsa Indonesia tercinta.
DAFTAR
PUSTAKA
Nontji, 2002. Laut
Nusantara. Jakarta: Anem Kosong Anem
PS, 2008. Agribisnis
Perikanan. Jakarta: Penebar Swadaya
Ritzer, Goodman. 2013. Teori Sosiologi. Jakarta: Kreasi Wacana
Fauzi, Anna. 2005. Pemodelan Sumber Daya Perikanan Dan Kelautan.Jakarta:PT.Gramedia
Pustaka utama
Asian Development Bank . 2011. Food For All. Philippines. Metro Manila
Ramat, 2015.
Memerangi Rawan Pangan. Kupang: Victory News
Ikhsan, Erwin dalam thesisnya yang berjudul “Politik Pangan di Maluku studi kasus
kebijakan tentang ketahanan pangan lokal di Maluku” tahun 2013
Jafar. “57
Kabupaten Di Indonesia Masih Rawan Pangan” dalam Jpnn.com (9/6/2015)







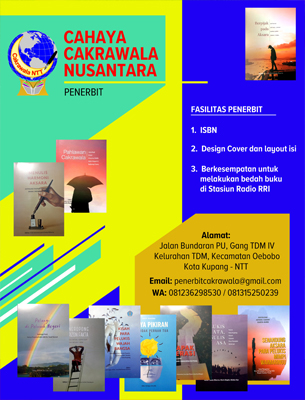










0 Comments